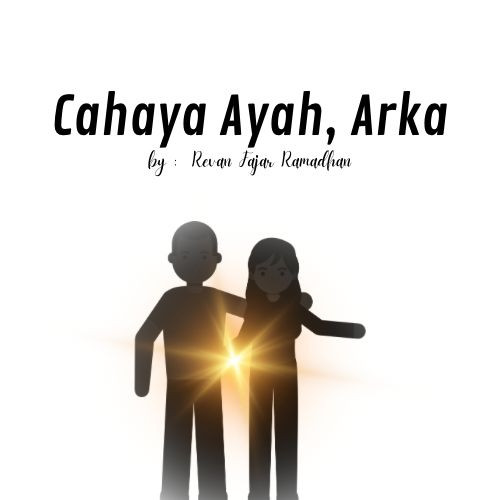Berita
- By Revan Fajar Ramadhan
- 22 Jan 2025
- 424
CAHAYA AYAH, ARKA...
Pagi itu,
Adit berlari tergesa-gesa menuju aula besar di kampus. Seminar tentang “Pengembangan
Infrastruktur” tengah berlangsung, dan ia sudah terlambat. Kopi panas di
tangannya sedikit bergetar saat ia mempercepat langkah. Tanpa sengaja, ia menabrak
seorang gadis di depan pintu masuk.
Kopi itu
tumpah, mencemari buku catatan yang dipegang gadis tersebut. “Aduh! Maaf
banget, aku nggak sengaja!” Ujar Adit panik sambil mengambil tisu.
Gadis itu
hanya tersenyum tipis. “Nggak apa-apa. Aku bisa catat ulang nanti.” Katanya tenang, meskipun halaman bukunya terlihat basah oleh noda cokelat.
Adit
terpana sejenak. Di balik rambut hitam panjang yang sedikit berantakan, wajah
gadis itu tampak teduh. “Aku Adit.” Ucapnya, berusaha memperbaiki situasi.
“Maya.” Balasnya
sambil menerima tisu yang ditawarkan Adit.
Pertemuan
yang canggung itu menjadi awal kisah mereka. Adit, mahasiswa Teknik Sipil yang
serius, menemukan kenyamanan dalam obrolan ringan bersama Maya, mahasiswi
Psikologi yang penuh perhatian. Dari diskusi tentang tugas kuliah hingga
percakapan mendalam tentang mimpi-mimpi, mereka semakin sering menghabiskan
waktu bersama. Perlahan, hubungan mereka berkembang dari teman menjadi lebih
dari itu.
Suatu
malam, di kafe kecil tempat mereka biasa menghabiskan waktu, Adit mengungkapkan
perasaannya. “Aku nggak tahu gimana caranya ngomong, tapi… aku suka kamu. Aku
ingin kita lebih dari sekadar teman.”
Maya
terdiam sejenak sebelum tersenyum. “Aku juga suka kamu, Dit. Aku mau kita
coba.”
Hubungan
mereka penuh kebahagiaan sederhana. Setelah beberapa tahun berpacaran, mereka
memutuskan untuk menikah. Pernikahan itu sederhana namun penuh kehangatan,
dikelilingi keluarga dan sahabat.
Tahun-tahun
awal pernikahan mereka adalah masa-masa indah. Mereka merencanakan banyak hal,
termasuk memiliki anak. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika setelah
setahun mencoba, Maya belum juga hamil.
Awalnya,
mereka berpikir bahwa semua akan terjadi pada waktunya. Namun, ketika
bulan-bulan berlalu tanpa hasil, mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan
dokter. Kabar yang mereka terima menghancurkan hati mereka. Ada masalah
kesehatan yang membuat peluang mereka untuk memiliki anak sangat kecil.
“Aku
merasa gagal jadi istri yang baik, Dit.” Kata Maya dengan suara bergetar suatu
malam.
Adit
menggenggam tangan Maya erat. “Kita punya satu sama lain. Itu cukup.”
Mereka mencoba berbagai cara—terapi medis, pengobatan alternatif, bahkan doa panjang setiap malam. Setelah bertahun-tahun berjuang, kabar bahagia akhirnya tiba. Maya hamil. Tangis bahagia pecah saat dokter mengonfirmasi kehamilannya. Adit tidak pernah merasa sebahagia itu sebelumnya.
Masa-masa
kehamilan Maya menjadi momen paling berharga dalam hidup mereka. Adit semakin
protektif terhadap Maya, memastikan ia makan makanan sehat, cukup istirahat,
dan menghindari hal-hal yang bisa membuatnya stres. Mereka menghitung hari
dengan penuh antusiasme, merencanakan segala sesuatu untuk menyambut sang bayi.
“Dit, aku
mau dekorasi kamar bayi kita bernuansa hutan, dengan warna hijau dan cokelat.” Kata
Maya sambil memperlihatkan beberapa gambar desain kamar bayi yang ia simpan di
ponselnya.
“Itu ide
bagus. Tapi jangan terlalu banyak boneka, ya. Aku nggak mau nanti dia malah
takut karena kamarnya terlalu ramai.” Jawab Adit sambil tersenyum.
Mereka
menghabiskan waktu memilih perlengkapan bayi. Maya terkadang tertawa geli
melihat Adit yang begitu serius membandingkan merek popok atau stroller. “Dit,
kamu lucu banget. Kayak lagi bikin perencanaan proyek besar.” Ledek Maya.
“Ya, ini
memang proyek besar. Proyek hidup kita,” Jawab Adit penuh kebanggaan.
Namun,
ada satu hal yang menjadi tantangan besar bagi mereka, memilih nama untuk bayi. Mereka ingin nama
yang bermakna, tapi tidak terlalu umum.
“Bagaimana
kalau kita pakai nama tradisional Jawa?” Usul Adit suatu malam.
Maya
mengangguk setuju. “Tapi jangan yang terlalu panjang, ya. Kasihan anaknya nanti
kalau harus mengisi formulir.”
Mereka
menulis beberapa opsi nama di buku catatan, seperti “Revan,” “Arka,” “Rakha,”
hingga “Aksara.” Namun, setiap kali mereka mendiskusikannya, pilihan itu selalu
berubah.
“Kenapa
nggak pakai ‘Arka’ aja? Artinya ‘cahaya’ atau ‘sinar’. Rasanya cocok, karena
dia akan jadi cahaya dalam hidup kita.” Kata Adit akhirnya.
Maya
tersenyum dan menyetujui. “Arka. Sederhana, tapi penuh makna.”
Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Arka yang masih dalam kandungan membuat hidup mereka terasa lebih penuh harapan. Mereka tak sabar menanti detik-detik kelahirannya.
Hari
kelahiran Arka pun tiba...
Hari
kelahiran Arka menjadi momen penuh haru. Tangisan bayi itu terdengar seperti
jawaban atas semua doa yang Adit dan Maya panjatkan selama bertahun-tahun. Maya
menggenggam jemari mungil Arka dengan tangan gemetar. “Adit, dia sempurna.” Bisiknya,
sambil menahan tangis bahagia.
Adit,
yang biasanya tidak mudah menangis, tak mampu berkata-kata. Ia hanya mengangguk
dan menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. “Selamat datang di dunia, cahaya
Ayah.” Katanya dengan suara parau, sebelum mencium kening bayi itu penuh kasih.
Sejak itu, hari-hari mereka berubah drastis. Rumah kecil mereka yang dulu sering sunyi kini dipenuhi tawa dan tangis bayi. Setiap malam tanpa tidur terasa ringan karena cinta yang mereka miliki untuk Arka. Adit sering terjaga sampai dini hari, mengganti popok Arka sambil berbisik, “Nggak apa-apa, Ayah di sini. Nanti kamu besar, kamu pasti jadi orang hebat.”
Ketika
Arka berusia satu tahun, ia mulai belajar berdiri dan berjalan. Maya akan
berdiri beberapa langkah di depan, menggoda Arka dengan mainan favoritnya,
sementara Adit dengan sabar menahan napas di belakang. Setiap langkah kecil
yang Arka ambil adalah kemenangan besar bagi mereka.
“Ayo,
sayang, cuma dua langkah lagi ke Bunda!” Seru Maya dengan antusias.
Arka
terjatuh berkali-kali, tapi ia selalu tertawa kecil sebelum mencoba lagi.
Ketika akhirnya ia berhasil berjalan ke pelukan Maya, Adit bertepuk tangan
keras, melompat-lompat seperti anak kecil. “Kamu hebat, Nak! Ayah bangga banget
sama kamu!”
Ketika
Arka berusia empat tahun, ia mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa.
Ia suka membantu Adit di kebun, meskipun hanya dengan sekop kecil di tangannya.
“Aku mau bikin taman yang besar buat Ayah sama Bunda nanti.” Katanya sambil
menggali tanah dengan semangat.
Di usia
ini, Arka juga sudah lancar berbicara, bahkan sering membuat Maya dan Adit
takjub dengan logikanya yang sederhana namun menggemaskan. Ia kerap bertanya,
“Kenapa bintang nggak jatuh ke bawah, Ayah?” atau “Kalau kita jalan terus, bisa
sampai ke ujung dunia nggak, Bunda?”
Namun,
ada satu pertanyaan yang membuat Maya merasa seperti tertikam. Malam itu,
sebelum tidur, Arka meringkuk di pelukan Maya sambil menatap wajah ibunya
dengan mata polos. “Bunda, kalau aku nggak ada, Ayah sama Bunda bakal sedih
nggak?”
Pertanyaan
itu membuat Maya terdiam sejenak, menahan napas. Jantungnya terasa seakan
berhenti berdetak. Ia memeluk Arka erat, berusaha menyembunyikan rasa takut
yang tiba-tiba menyeruak dalam dirinya. Dengan suara bergetar, Maya menjawab,
“Bunda nggak mau kamu pergi kemana-mana, Nak. Kamu harus selalu di sini sama
Ayah dan Bunda.”
Di usia
lima tahun, Arka mulai menunjukkan minat pada dunia Maya. Ia sering meniru
ibunya menulis di buku catatan, mencoret-coret dengan penuh semangat. “Ini
cerita aku, Bunda.” Katanya sambil menunjukkan lembaran penuh coretan tak
beraturan. “Cerita tentang Ayah, Bunda, dan aku.”
Keseharian
Arka menjadi momen yang selalu menghangatkan hati Maya dan Adit, meskipun
bayangan kekhawatiran mulai menghantui mereka. Ia sering bernyanyi lagu
anak-anak dengan suara kecilnya yang ceria, mengisi sudut-sudut rumah dengan
tawa yang tak pernah mereka bayangkan akan sirna begitu cepat.
Namun, ketika Arka mendekati ulang tahunnya yang keemam, senyumnya mulai terasa berbeda. Tubuhnya yang biasanya penuh energi tiba-tiba terlihat lebih sering lelah. Adit dan Maya sempat mengira ini hanyalah efek dari hari-hari bermain yang terlalu padat, tetapi ketika demamnya tak kunjung turun dan ia sering mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya, mereka memutuskan untuk membawanya ke dokter.
Hasil
diagnosis itu seperti pukulan telak yang menghancurkan dunia mereka. Dokter
mengungkapkan bahwa Arka menderita penyakit autoimun langka yang menyerang
sistem tubuhnya. Harapan untuk sembuh hanya tersisa dalam bentuk terapi yang
bisa memperlambat, tapi tidak menyembuhkan.
Di
perjalanan pulang, Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ia menggenggam tangan Arka
erat-erat, sementara anak itu tertidur di kursi belakang mobil. Adit, yang
biasanya tegar, menggigit bibirnya sampai hampir berdarah untuk menahan tangis.
“Kenapa harus dia?” Bisiknya lirih, matanya tetap terpaku pada jalanan di
depannya.
Meski
dihantui rasa takut, mereka memutuskan untuk tidak menunjukkan kesedihan di
depan Arka. Setiap harinya, mereka berusaha membuatnya tetap merasa seperti
anak-anak lainnya. Mereka merayakan ulang tahunnya yang kelima dengan
sederhana, tapi penuh cinta.
“Arka,
mau hadiah apa di ulang tahunmu kali ini?” Tanya Adit, mencoba menyembunyikan
rasa perih di dadanya.
Arka,
yang duduk dengan tubuh semakin kurus tapi masih tersenyum ceria, menjawab,
“Aku mau main ayunan di taman. Bunda sama Ayah ikut ya?”
Hari itu,
mereka membawa Arka ke taman dekat rumah. Adit mendorong ayunan perlahan,
sementara Maya duduk di samping mereka, berusaha mengabadikan momen itu di
dalam ingatannya. Arka tertawa kecil, kepalanya menengadah ke langit. “Ayah,
Bunda, kalau aku besar nanti, aku mau bangun taman ini jadi lebih indah. Ada
bunga warna-warni, ada kolam kecil, dan banyak burung yang terbang di atas.”
Adit
tersenyum, meski hatinya terasa seperti remuk. “Tentu, Nak. Kamu pasti bisa.”
Tapi
malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Maya menangis tersedu-sedu di dalam
kamar mandi, menutup mulutnya agar suara tangisnya tidak terdengar. “Kenapa
harus Arka, Tuhan? Kenapa anak sekecil dia harus melalui ini?”
Seiring
waktu, kondisi Arka semakin memburuk. Tubuhnya menjadi semakin lemah, dan ia
lebih sering terbaring di tempat tidur. Namun, ia tetap menunjukkan senyumnya.
Suatu hari, ketika Adit sedang membacakan buku cerita favoritnya, Arka
tiba-tiba berkata, “Ayah, kalau aku nggak ada nanti, Ayah sama Bunda nggak
boleh sedih ya. Aku nggak mau kalian nangis terus.”
Adit menahan tangisnya sekuat tenaga, menggenggam tangan mungil Arka. “Ayah sama Bunda nggak akan pernah lupa sama kamu, Nak. Kamu selalu ada di hati kami.”
Di minggu
terakhirnya, Arka meminta Maya untuk menulis sesuatu di buku catatan kecilnya.
“Bunda, tulis ini ya. ‘Arka sayang Ayah dan Bunda, selamanya.’” Maya menulisnya
dengan tangan bergetar, air matanya jatuh mengenai kertas.
Arka
berpulang pada malam yang sunyi, di pelukan Maya dengan Adit yang memegang
tangan mereka berdua. Tangis Maya memenuhi ruangan, sementara Adit memeluk
keduanya erat, seakan tak ingin melepaskan keluarga kecilnya.